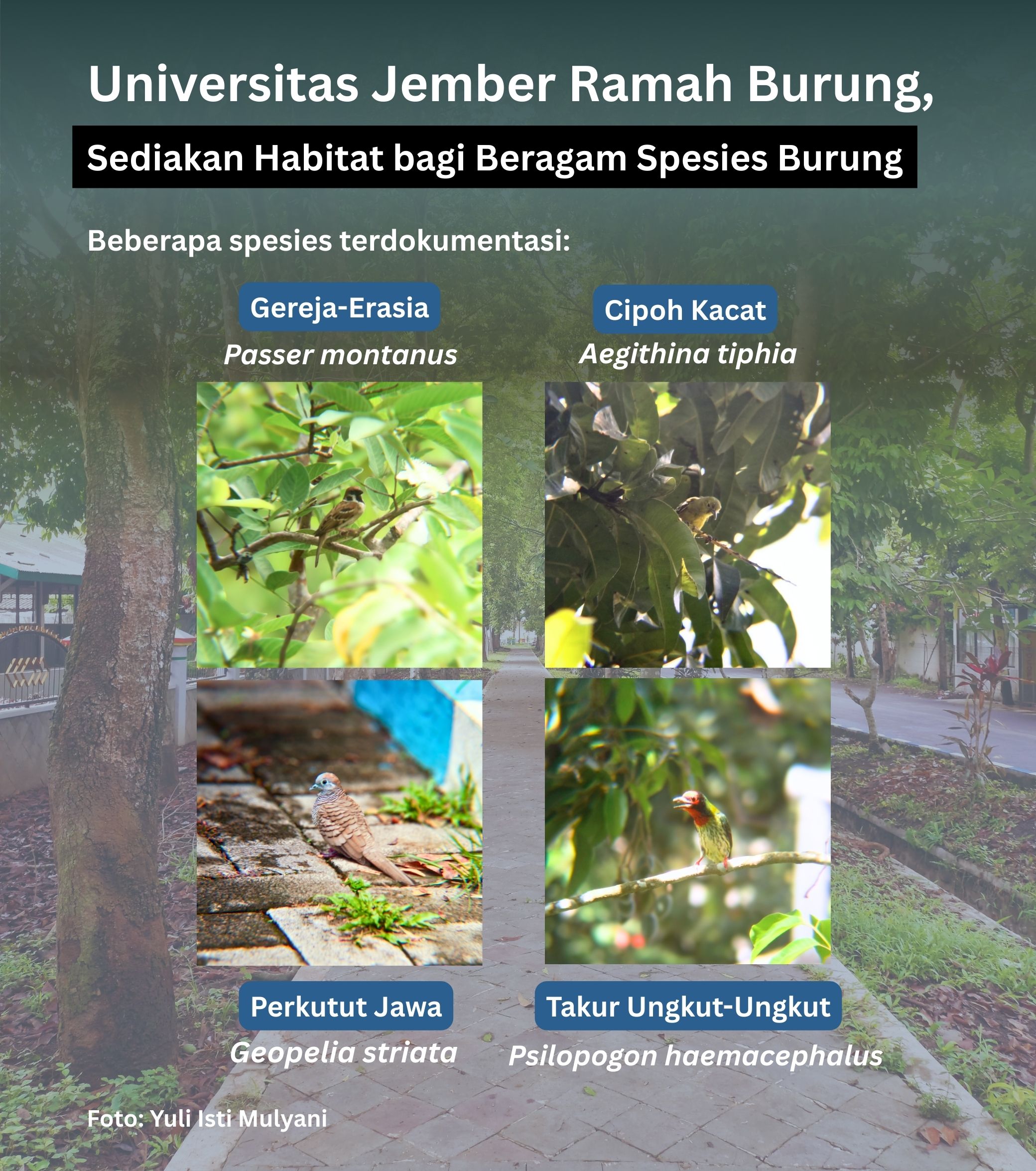Dampak Karhutla Terhadap Habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus)

(https://jurnalbumi.com/knol/gajah-sumatera/gajah-sumatera-2/)
Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan jenis mamalia besar yang tersebar di sepanjang Pulau Sumatera. Lembaga konservasi dunia yaitu International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) menetapkan status Gajah Sumatera dalam kondisi kritis (critically endangered) (WWF, 2013). Spesies tersebut juga terdaftar dikategori Apendiks I dalam Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora (CITES) yaitu jenis spesies yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah (CITES, 2012). Di Indonesia, Gajah Sumatera juga masuk dalam satwa dilindungi menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu PP 7/1999 tentang Pengawetaan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2007).
Informasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 1993 menyebutkan bahwa populasi gajah sumatera diperkirakan antara 2.800 sampai 4.800 ekor (44 kelompok) dengan penyebaran di Lampung 13 kelompok, Sumatera Selatan 8 kelompok, Jambi 5 kelompok, Bengkulu 2 kelompok, Riau 11 kelompok, Sumatera Barat 1 kelompok dan Sumatera Utara bagian barat dan Aceh 4 kelompok (Sinaga, 2001). Namun jumlah ini diperkirakan terus menurun akibat penangkapan, perburuan liar dan konversi hutan untuk berbagai kepentingan (Hedges et al., 2002; Nyhus dan Tilson, 2004). Penyempitan habitat alami gajah juga diakibatkan oleh aktivitas manusia lainnya seperti penebangan kayu dan pembakaran lahan yang berakibat pada perubahan kemampuan lahan dalam menampung jumlah gajah sumatera dalam habitat yang terdiri dari faktor biologis dan faktor fisik (Abdullah et al., 2009). Habitat menyediakan vegetasi sebagai pakan yang merupakan faktor utama satwa liar bertahan hidup. Gajah sumatera merupakan satwa herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Jenis makanan gajah antara lain rumput-rumputan, daun, liana, akar, rotan muda, pisang-pisangan, bambu, pakis, nibung (Mahanani, A. I., 2012). Selain penggunaan habitat sebagai tempat penyediaan pakan, gajah sumatera juga melakukan beberapa aktivitas sosial seperti hidup berkelompok dan menjelajah. Secara alami gajah melakukan penjelajahan dengan berkelompok mengikuti jalur tertentu yang tetap dalam satu tahun penjelajahan. Jarak jelajah gajah bisa mencapai 7 km dalam satu malam, bahkan pada musim kering atau musim buah-buahan di hutan mampu mencapai 15 km per hari (WWF, 2006). Gajah terutama menggunakan habitat spesifik yaitu hutan tertutup basah permanen dengan aksesibilitas tinggi. Gajah lebih sering menggunakan habitat dengan ciri berjarak dekat ke hutan, kemiringan landai, terdapat pohon gesek badan, dan tidak dijumpai herbivor besar lainnya. Sebagian besar aktivitas gajah dilakukan di hutan primer (berlindung, istirahat, interaksi sosial dan reproduksi) namun lebih banyak menghabiskan waktu untuk makan di hutan sekunder (abdullah, 2009). Menurut pengamatan yang dilakukan oleh Nyhus dan Tilson (2004) di Taman Nasional Way Kambas juga menyebutkan bahwa menggunakan habitat hutan primer sedangkan padang rumput hanya digunakan untuk menuju ke unit habitat lain.
Kerusakan habitat yang terjadi akhir-akhir ini berupa kebakaran hutan di beberapa tempat tentu memberi dampak buruk terhadap kelangsungan hidup satwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dalam kurun Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare (Ha). Daerah yang terdampak paling luas yakni Riau (https://tirto.id/ehQg). Kebakaran hutan merupakan bencana bagi keanekaragaman hayati. Tak terhitung berapa jumlah spesies tumbuhan dan plasma nutfah yang hilang. Vegetasi yang rusak menyebabkan hutan tidak bisa menjalankan fungsi ekologisnya secara maksimal. Juga menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa liar penghuni hutan (Fikri, F, 2012). Sementara itu dari data MENLHK (https://dataalam.menlhk.go.id/luaskawasan) Informasi Luas Kawasan terutama Luas Lahan Hutan (%) dari tahun 2018 hingga 2019 memaparkan bahwa Luas Lahan Hutan Aceh turun dari (60,5% - 8,3%), Sumatera Utara (20,9% - Tidak ada data), Sumatera selatan (35,4% - 0,4%), Sumatera Barat (35,6% - 34,0%), Riau (14,3% - Tidak ada data), Jambi (45,9% - 65,7%), Bengkulu (Tidak ada data - 26,6%), Lampung (29,0% - 19,3%). Hal ini menunjukan sebagian besar terjadi penurunan luas lahan hutan pada daerah yang merupakan habitat bagi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus).
Referensi:
Abdullah. 2009. Penggunaan Habitat dan Sumber Daya oleh GajahSumatera (Elephas maximus sumatranus Temminck, 1847) di Hutan Prov. NAD Menggunakan Teknik GIS. Berk. Penel. Hayati Edisi Khusus: 3B (47–54).
Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora (CITES). 2012. Elephas maximus sumatranus. (online), (http://www.cites.org/eng/results.php?cites=Elephas+maximus+sumatranus) ,diakses 15 Oktober 2019.
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2007. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017. Departemen Kehutanan RI. (online), (https://jurnalbumi.com/knol/gajah-sumatera/#return-note-257-11), diakses 15 Oktober 2019.
Fikri, F. 2012. Dampak Asap Kebakaran Hutan pada Pernapasan. CDK-189/ vol. 39 no. 1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Informasi Luas Kawasan, Data alam. (online), (https://dataalam.menlhk.go.id/luaskawasan), diakses 15 Oktober 2019.
https://jurnalbumi.com/knol/gajah-sumatera/gajah-sumatera-2/
Mahanani, A.I. 2012. Strategi Konservasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus Temminck) di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Daya Dukung Habitat. Tesis. Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
Nyhus, P., dan Tilson, R. 2004. Agroforestry, Elephant and Tiger: Balancing Conservation Theory and Practice in Human Dominated Landscape of Southeast Asia, Agricultural Ecosystem and Environment, 104, 87–97. Sinaga, W.H. 2001. Pelestarian Gajah Sumatera, Antara Harapan dengan Kenyataan. http:www.warsi.or.id /asp/edisi10/ asp10_16.htm.
WWF, Balai KSDA Provinsi Riau. 2006. Protokol Pengurangan Konflik GajahSumatera di Riau.
Leave a Reply
Terkait